Ditolak lagi, ditolak lagi.
Malu tapi Maju ke-47 | Bukan, bukan ditolak pas nembak.
Senin pagi, gue buka laptop. Email dari client udah nunggu di inbox: “Terima kasih atas pitch presentationnya kemarin. Setelah diskusi internal, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan kalian. Terima kasih atas segala kerja kerasnya, semoga bisa bekerjasama dilain kesempatan.”
Langsung lemes.
Padahal kemarin presentasinya lancar. Client juga responnya positif. Banyak nanya (sign positif). Gue udah bayangin kalo fee-nya masuk, udah gue itung-itung mau dipake buat outing sama anak-anak. Eh ternyata ditolak.
Yang bikin sakit bukan cuma soal duitnya (walaupun ya... sakit juga sih wkwk). Tapi rasanya kayak, “Dih apaan sih gue? Kok gagal mulu?”
Ini cerita 6-7 taun lalu. Sekarang kalo ditolak client, gue masih kecewa, tapi nggak sampe ngerasa kayak failure as a human being. Dulu mah iya banget, every rejection gue take it personally. Every rejection itu gue anggap sebagai orang menolak gue sebagai manusia. Nara = ngga gue terima.
Contohnya, pernah ada klien yang bilang proposal gue “kurang kreatif.” Langsung kepikiran: “Gue orangnya ga kreatif dong. Gue ga cocok kerja di bidang ini. Mending gue cari karir lain aja.” Lol. Drama bgt dah dulu.
Padahal sekarang kalo dipikir-pikir, yang mereka tolak itu cuma satu proposal. Atau satu pitch. Atau satu konten. Bukan gue sebagai manusia. Bukan kemampuan gue secara keseluruhan. Bukan pengalaman yang gue punya, bukan wisdom yang gue kumpulin. Cuma satu ide yang emang mungkin belum pas sama expectation mereka.
Tapi dulu? Wah, langsung nyungsep ke self-doubt yang dalem banget.
Nah, dari sini gue mulai nyari-nyari cara buat ngehadapin pola pikir yang toxic ini. Masa iya setiap kali ditolak gue harus drama kayak sinetron wkwk.
Kebetulan di masa-masa itu gue lagi sering-seringnya consume apapun tentang self-development, dan salah satunya yang gue suka banget adalah podcastnya Tim Ferris. Gue ketemu konsep Stoicism dari doi. Dia bikin ebook gratis tentang Seneca, The Tao of Seneca. Pas gue baca-baca itu, ada satu filosofi yang langsung kena: cara mereka ngeliat masalah itu bukan sebagai sesuatu yang terjadi “pada” kita, tapi sebagai sesuatu yang kita bisa control responnya.
Salah satu konsep utama adalah dichotomy of control, yaitu membedakan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Yang bisa kita kontrol adalah usaha kita, baik itu dalam bikin pitch deck, nanya-nanya ke klien, seberapa keras kita bekerja, atau seberapa bagus kita present. Itu semua berada dalam kendali kita.
Yang nggak bisa kita kontrol adalah keputusan klien, budget mereka, timing, politik internal, kompetitor, dan hal‑hal serupa. Ini ga usah kita pusingin, karena toh ga bisa kita apa-apain juga.
Memahami ini juga bikin kalau berhasil, kita ga sombong dan sotoy, kita harus inget bahwa ada pengaruh dari hal yang ga kita kontrol.
Disisi lain, kalau kalah dan ditolak, bikin kita juga ga terlalu berkecil hati, karena toh emang ada hal yang ga bisa kita kontrol juga. Ini bikin gue lebih legowo.
Yang bikin konsep ini makin ngena buat gue adalah karena ternyata mirip banget sama yang gue tau dari agama yang gue anut. Sebagai muslim (yang masih belajar), gue familiar sama konsep ikhtiar dan ikhlas. Ikhtiar = usaha maksimal di hal yang bisa kita kontrol. Ikhlas = nerima hasil yang datang, karena ada faktor-faktor di luar kendali kita yang cuma Allah yang tau.
Pas gue sadar paralel ini, everything clicked. Stoicism ngasih gue framework yang praktis, tapi pondasi spiritualnya udah ada dari dulu. Ga heran rasanya natural.
Jadi sekarang kalau lagi pitch: gue ikhtiar maksimal (persiapan, riset klien, bikin deck yang bagus), terus ikhlas sama hasilnya. Kalau ditolak, ya mungkin emang ada hikmah atau timing yang belum tepat. Kalau diterima, alhamdulillah, tapi tetep inget ini bukan cuma karena kemampuan gue doang.
Simple di teori, susah di eksekusi.
Nah, dari framework ikhtiar-ikhlas dan dichotomy of control ini, gue sadar ada satu hal penting yang sering kita skip: feedback.
Kenapa feedback penting dalam konteks ini? Karena feedback itu bridge antara yang bisa kita kontrol dan yang ga bisa. Data rejection bisa jadi input untuk improve ikhtiar kita next time.
Sebisa mungkin kalau ditolak, cari tahu feedbacknya apa.
Ini yang paling susah. Ego gue tuh pengen langsung move on pas ditolak. “Ah, mereka aja yang ga ngerti.”
Tapi kalo gue paksa diri gue untuk nanya feedback, sering banget dapet insight yang valuable. Pernah ada klien yang nolak proposal gue, tapi pas gue follow up nanya kenapa, ternyata timing-nya aja yang ga pas. Budget mereka lagi di freeze sama management.
Bukan karena proposal-nya jelek.
Kalo gue ga nanya, sampe sekarang mungkin masih taunya “specific strategy gue di pitch itu ga works” padahal sebenernya bukan itu masalahnya.
Feedback ini jadi cara gue ngebedain mana rejection yang emang karena kerjaan gue kurang bagus (bisa diperbaiki untuk next time), mana yang emang karena faktor eksternal (ga usah diambil hati). Tanpa feedback, semua rejection berasa sama aja: personal attack ke gue sebagai manusia.
Sekarang kalo gue ditolak, prosesnya kurang lebih gini:
Kecewa dulu 5-10 menit. Aman aja, manusiawi.
Inget: yang ditolak itu karya gue, bukan gue sebagai manusia.
Reflect: udah maksimal belum effort gue? Kalo udah, ya udah lepas.
Cari feedback. Even if it hurts.
Learn, improve, next.
Ga selalu mulus prosesnya. Kadang masih stuck di step 1 lebih lama dari yang gue mau wkwk. Ini aja sekarang gue masih stuck dan baru aja mau move on karena tools personal branding gue receptionnya ga sebagus bayangan gue. Tapi setidaknya sekarang ada framework-nya.
Yang pasti, setiap rejection yang gue dapet gue usahain banget untuk gue treat sebagai data. Bukan sebagai verdict tentang worth gue sebagai manusia. Akibatnya hati jadi lebih enteng. Ini works di gue, belum tentu works di elo. Ambil yang bagus-bagusnya aja yak.
The updated version of my favorite modern philosopher talking about wealth, Naval Ravikant. Selain ini isinya rapet banget daging semua, gue masih amazed dia bisa ngomong spontan daging semua tanpa filler words (mmm.., eh…, etc)
Ini adalah campaign paling barunya Claude. Salah satu competitor Open AI, yang punya ChatGPT. Gue suka banget positioningnya Claude yang AI sebagai pembantu kita untuk mikirin hal-hal yang menarik. Taste dan aestheticnya juga oke bangettt. Sangat “anti-slop”.
Biyutiful. I blindly agree with this take.
Semoga isi newsletter kali ini berguna, atau menghibur atau sekedar untuk spik-spik ke kolega atau bosmu ya.
Kalau lo mau value lebih:
Tools untuk bikin customized Personal Branding Strategy + Content Ideation Generator + Courses:
https://personalbranding.id/ (Paid)
Free Content Pillar generator:
https://contentpillar.id/ (Free)
Resources untuk manage Imposter Syndrome: https://bit.ly/managing-imposter (Free)
Belajar Marketing Foundation lewat pre-recorded course: https://clicky.id/botakasu/marketing-foundation (Paid)




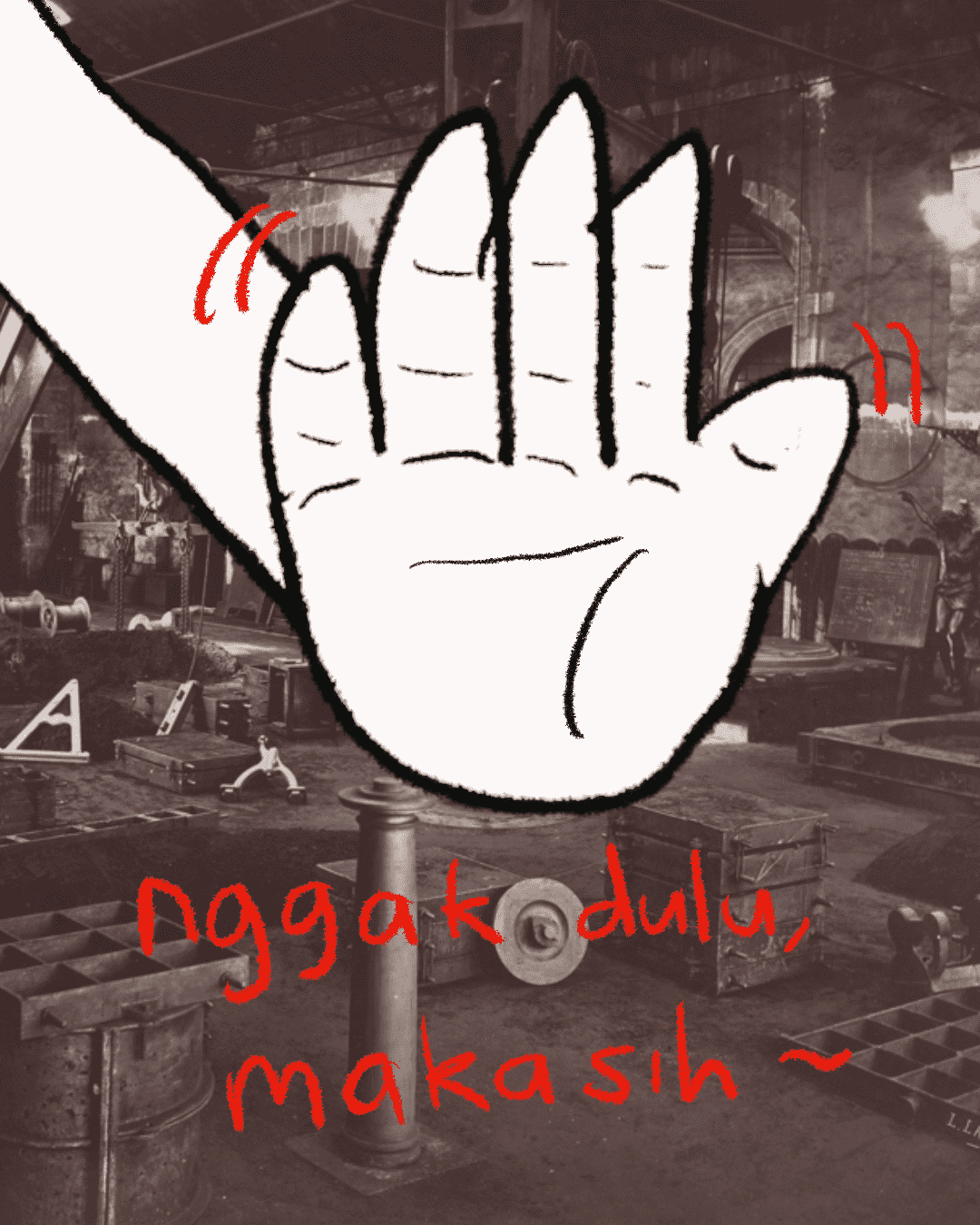


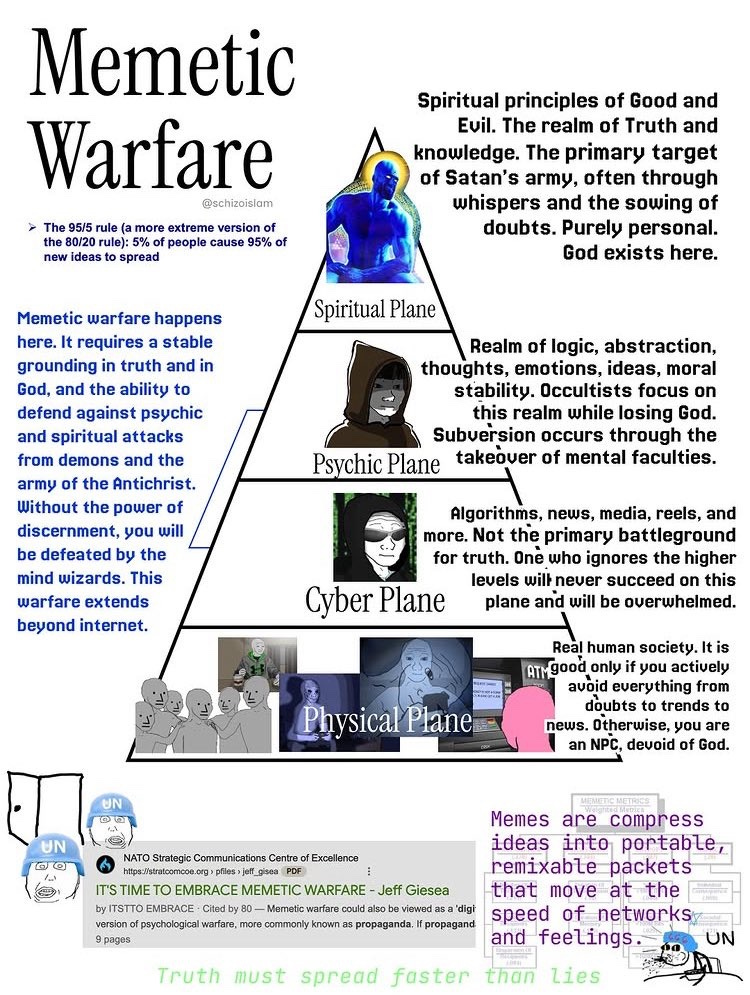



Saya bacanya pas banget udah nyampe kantor. Dari dulu masih jadi PR untuk gimana caranya biar enggak take personally kalau ditolak, rasanya jadi kayak terobsesi banget untuk diterima dan enggak mau ditolak. Thanks, Bang, insight-nya daging banget!